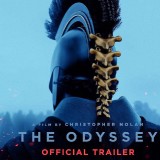TIMES PINRANG, SURABAYA – Perubahan besar sedang terjadi di dunia kampus. Bukan lagi sekadar soal metode belajar daring atau ujian berbasis komputer, tetapi tentang bagaimana mahasiswa kini mulai menulis dengan bantuan kecerdasan buatan (AI). Seperti ChatGPT, Gemini, atau Copilot menjadi teman baru di balik layar.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah AI sedang membantu mahasiswa berpikir, atau justru mengambil alih cara mereka bernalar?
TIMES Indonesia berkesempatan berbincang dengan Dr. H. Yusuf Amrozi, M.MT, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kini tengah fokus meneliti perilaku literasi digital mahasiswa di era kecerdasan buatan.
Yusuf Amrozi berbicara terbuka tentang bagaimana kampus seharusnya tidak menolak AI, tetapi menyiapkan pagar etik dan kesadaran kritis dalam pemanfaatannya.
Berikut petikan lengkap wawancaranya.
Pak Yusuf, apa pandangan Anda tentang tren mahasiswa menulis menggunakan AI untuk menulis tugas akademik?
Jadi begini AI sebagai bagian dari temuan peradaban mutakhir tidak bisa di lawan atau ditolak. Tetapi bagaimana kampus atau lembaga pendidikan harus mensiasatinya untuk kepentingan yang positif.
Menurut Anda, sejauh mana AI bisa dianggap sebagai alat bantu belajar, bukan pelanggaran akademik?
Saya memiliki keyakinan bahwa hari ini tidak ada orang yang tidak menggunakan AI untuk mencari jawaban atas suatu yang ditanyakan, atau meminta bantuan lainnya melalui AI, apalagi peserta didik (siswa dan mahasiswa).
Maka dari itu, tinggal bagaimana institusi pendidikan membuat regulasi yang disatu sisi mendayagunakan AI tersebut tetapi disisi lain mengedukasi peserta didik, termasuk misalnya kemampuan untuk memvalidasi konten hasil generate AI.
Apa perbedaan mendasar antara mahasiswa yang menulis dengan bantuan AI dan yang menulis secara manual dalam hal kualitas berpikir?
Umumnya bagi mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) kemampuannya dalam menarasikan kalimat pada suatu karya akademik biasanya lebih baik. Meskipun juga ada mahasiswa S1 yang memiliki kemampuan penarasian yang baik dan sistematis. Sehingga dalam konteks ini saya ingin mengatakan bahwa kualitas hasil generate AI ibaratnya sdh selevel dengan perumusan dari mahasiswa pasca.
Nah, berdasarkan hal ini dosen dapat melakukan tracking melalui alat bantu perangkat lunak terkait, atau melakukan validasi/wawancara terhadap mahasiswa tersebut terhadap isi makalah atau karya tulis yang ia buat. Serta rujukan yang dipakai. (kalau saya harus ada rujukan yang sahih, statemen itu didasarkan dari jurnal mana, artikelnya siapa/dari referensi apa, dst).
Apa risiko terbesar dari ketergantungan mahasiswa pada AI dalam menulis karya ilmiah?
Resiko terbesar dari AI adalah mahasiswa akan sangat tergantung dengan AI serta tidak memiliki kemampuan untuk berfikir, menuangkan gagasan, berpendapat hingga dalam pengambilan keputusan sehari hari dalam hidupnya secara mandiri. Semuanya berharap dari chatbox di AI.
Apa langkah ideal yang harus dilakukan kampus untuk menyeimbangkan penggunaan AI dengan prinsip kejujuran akademik?
Menurut hemat saya, kampus harus membuat pedoman operasional dan kode etik terkait tata tulis ilmiah. Biasanya didalamnya ada klausul tingkat similirity yang boleh ditolelir.
Pada prinsipnya, saya termasuk sebagai pendidik yang pro penggunaan AI untuk mengenerate ide atau membantu penyelesaian tugas akademik untuk menjamin kompetensi mahasiswa.
Tetapi mahasiswa harus tetap dididik untuk bisa melakukan validasi atas kebenaran yang ditawarkan AI serta penarasian final dari suatu gagasan atau pemikiran yang disampaikan oleh mahasiswa (penarasian final/peredaksionalan oleh mahasiswa tsb).
Siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengedukasi mahasiswa agar menggunakan AI secara etis: dosen, kampus, atau mahasiswa itu sendiri?
Semua pihak harus terlibat. Dan diawali oleh regulasi. Kalau di kampus biasanya leading sector nya pejabatnya yang berurusan dengan akademik, yang punya andil atau wewenang untuk itu.
Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari praktik mahasiswa menulis dengan AI?
Untung rugi dalam hal ini tidak dlm konteks nilai mata uang. Bagi user (pengguna: dosen/mahasiswa/siapapun) keuntungannya bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Tetapi celakanya, jika sangat tergantung dan pasrah bongkok an dengan AI ini kita akan mengalami keterbelakangan mental dan berfikir, dalam bersikap dan bertindak. Vendor AI, atau secara umum produsen IT yang mendapat benefit dari produk yang banyak diminati oleh pasar tersebut.
Kapan Anda mulai menyadari perubahan pola menulis mahasiswa akibat hadirnya teknologi AI?
Secara empiris dua tahun belakangan, senyampang maraknya aplikasi chatbox AI ini.
Kapan menurut Anda penggunaan AI perlu mulai diajarkan secara formal dalam kurikulum sistem informasi?
Saya kira urgensi adopsi AI tidak hanya untuk mahasiswa bidang IT saja (memang koding dapat dihasilkan dari memberi perintah/promting di chatbox AI). Tetapi perlu diajarkan di jurusan lain. Nama matkulnya biasanya literasi digital dan tata tulis ilmiah.
Tetapi menurut saya penamaanya bisa “dinaikkan” menjadi Literasi AI. Disana juga ditegaskan materi atau pokok bahasan tentang kode etik atau rambu-rambu berliterasi menggunakan AI. Tetapi yang pasti bahwa aplikasi yang bernuansa AI tidak semata chatbox AI spt chatGPT, Copilot, Gemini dan ratusan lainnya.
Dalam kepentingan akademik saat ini banyak aplikasi untuk sejumlah kepentingan misalnya: mereview sejumlah artikel jurnal dan mensintesiskannya, melakukan olah data penelitian, pemetaan konsep dan terminologi (mind maping), software untuk reference manager, dan lainnya.
Kapan batas toleransi penggunaan AI dianggap melewati garis etika akademik menurut Anda?
Sampai yang bersangkutan tidak memiliki “kesadaran” tentang apa yang disampaikan tersebut. Artinya dia sudah tidak lagi memiliki kemampuan berargumen yang logis sesuai narasi atau karya yang disodorkan tersebut. Serta tidak ada media validasi atas karya tersebut, atau dalam bahasa lain tidak layak berdasarkan validasi. (perangkat lunak dapat digunakan untuk membantu validasi)
Di mana posisi Prodi Sistem Informasi dalam mengawal transformasi digital literasi menulis di kampus?
Sebagai prodi dalam bidang rumpun teknik dan cabang ilmu formal, prodi ini tentu memiliki tanggungjawab lebih (dosen dan mahasiswanya) untuk menjadi leader dalam menegakkan tata etika pemanfaatan IT.
Saya mengajar di matakuliah Konsep Sistem Informasi di Prodi Sistem Informasi Fak Saintek UIN Sunan Ampel Surabaya. Matkul ini sebagai matkul pembuka di semester satu. Didalamnya ada pokok bahasan seputar etika pemanfaatan IT.
Salah satu tugas pada capaian pembelajaran (learning outcomes) nya adalah mahasiswa membuat video pendek tentang kampanye berinternet sehat atau kampanye internet positif. Video tersebut diunggah di youtube atau sosmed lainnya, sebagai media untuk mengedukasi publik agar menggunakan gadget nya secara bijak.
Sisi baiknya dari cara ini secara ndak langsung juga mendidik mereka menjadi content creator, yang berpotensi menghasilkan cuan/entrepreneur.
Di mana menurut Anda titik rawan penyalahgunaan AI paling sering terjadi di lingkungan akademik?
Biasanya saat mereka mengerjakan tugas akademik (makalah/artikel/membuat laporan riset)
Mengapa sebagian dosen menolak penggunaan AI dalam proses akademik padahal teknologi ini sudah menjadi bagian kehidupan digital?
Mungkin ada, tetapi sy tidak tau persis alasannya
Mengapa kemampuan berpikir kritis tetap penting meskipun mahasiswa sudah bisa menulis dengan bantuan AI?
Salah satu ukuran IQ menurut saya adalah kemampuan melakukan inferencing atau melakukan sintesa atau melakukan penarikan kesimpulan. Maka basis modalnya adalah kemampuan kritik analitik. Oleh karena itu critical thinking tetap menjadi kunci.
Mengapa regulasi etika AI di kampus masih terbilang lambat dibandingkan dengan cepatnya perkembangan teknologi?
Sebagai lembaga, kampus yang diurusi tidak hanya akademik. Mulai dari administrasi, akreditasi, reputasi kinerja tridharma, dan lainnya. Sementara teknologi berubah sangat cepat. Namun demikian regulasi seputar pemanfaatan AI juga harus segera mendapat perhatian dari pimpinan kampus atau kementerian.
Bagaimana Anda menilai kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan AI secara kreatif dan bertanggung jawab?
Masing-masing kondisi dan sumberdaya di tiap kampus meang beda, termasuk mahasiswanya. Tetapi sebagai mahasiswa bidang IT anak-anak Sistem Informasi tentunya terbiasa berfikir HOTS (high order thinking skills)
Bagaimana strategi kampus atau prodi Anda dalam membimbing mahasiswa agar tidak menjadikan AI sebagai “jalan pintas”?
Kata kuncinya adalah produk akademik ada rujukan yang bisa di verifikasi. Semakin baik referensi yang digunakan, ditambah dengan data dan kemampuan dalam menarik simpulan, maka kualitas karya akademik mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan. Dan sedari awal anak-anak kami biasanya kami triger dengan membuat karya akademik (artikel) bahkan sejak semester satu atau dibiasakan menulis.
Bagaimana Anda melihat masa depan penulisan akademik di era AI, apakah akan melahirkan generasi penulis yang lebih inovatif, atau justru kehilangan karakter orisinalitasnya?
Tergantung. Kalau kita sebagai pendidik lepas tangan, ya mereka akan semakin disorientasi. Tetapi manakala sedari awal dibimbing dengan menggunakan sumberdaya digital secara benar, maka insyaallah mereka akan lulus dengan kompetensi sesuai jurusannya serta menemukan invensi pada masa mereka duduk dijenjang pendidikan tinggi tersebut. (*)
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: Dr. Yusuf Amrozi: Tren Mahasiswa Menulis dengan AI Tak Bisa di Tolak
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |